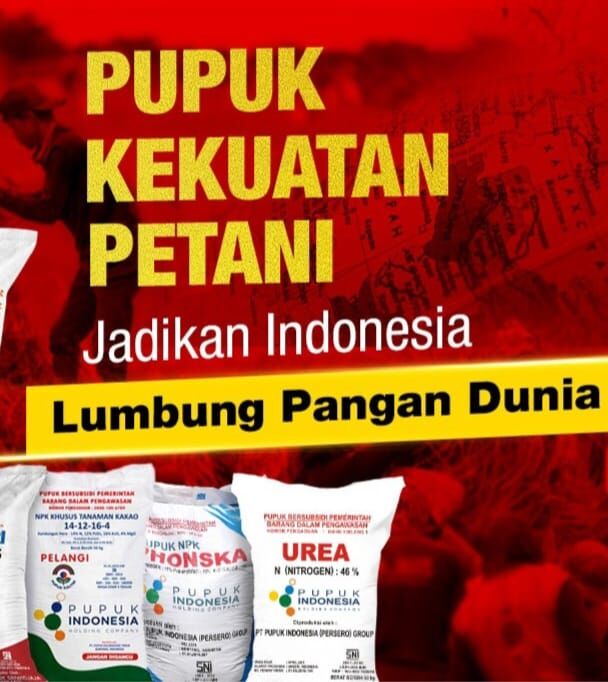Oleh Muliadi Saleh
Detikpangan.com – Pangan, hakikatnya bukan hanya urusan perut. Ia adalah bahasa kebudayaan yang paling tua dan paling jujur. Dari padi yang ditanam bersama doa, hingga roti yang dibakar dengan keyakinan, manusia membangun peradaban melalui dapur dan ladang sebelum melalui gedung dan laboratorium. Tak heran, banyak filsuf dan sufi menempatkan pangan dalam wilayah spiritualitas. “Apa yang kau makan, itulah yang akan menjadi dirimu,” kata Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin.
ADVERTISEMENT
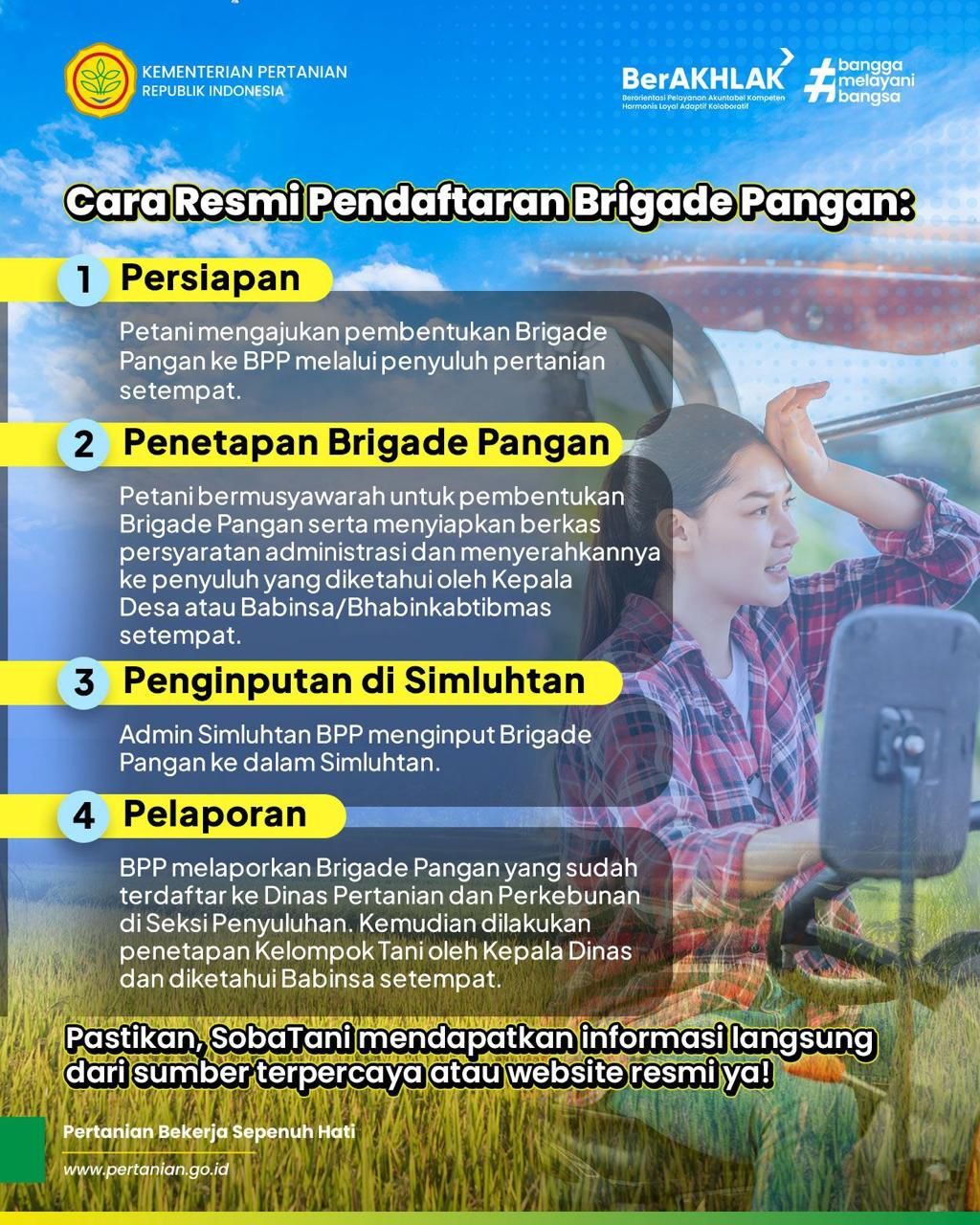
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketika tersaji sepiring nasi, sesungguhnya kita sedang menatap sejarah panjang perjuangan manusia—para petani yang berpeluh di sawah, air yang mengalir dari gunung, tangan-tangan yang menumbuk, menanak, dan menyajikan dengan cinta. Maka, setiap suapan seharusnya adalah zikir, bukan sekadar kebiasaan. Ada kesadaran spiritual di dalamnya: bahwa makan bukan sekadar memenuhi kebutuhan biologis, tapi meneguhkan hubungan manusia dengan bumi dan Tuhan.
Namun di tengah arus modernitas, makna itu perlahan memudar. Pangan direduksi menjadi komoditas, bukan kebudayaan. Kita mulai lupa pada asal, kehilangan jejak dari tanah yang memberi. Makanan cepat saji menggantikan jamuan penuh doa. Anak-anak tak lagi tahu aroma padi yang baru dituai. Di supermarket, pangan tampil steril, seolah lahir tanpa petani, tanpa peluh, tanpa musim.
Padahal politik pangan sejatinya adalah politik kemanusiaan. Bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang berdaulat atas makannya. Jika beras, jagung, kedelai, bahkan garam pun harus diimpor, maka yang hilang bukan hanya kemampuan bertani, tetapi juga martabat dan kemandirian. Petani yang ditinggalkan adalah tanda peradaban yang pincang; sebab mereka sejatinya adalah penjaga dapur bangsa.
Pangan mencerminkan ideologi. Ketika sebuah bangsa menempatkan petani sebagai warga kelas dua, maka sesungguhnya ia sedang mengubur akar sejarahnya sendiri. Sebaliknya, bangsa yang menghormati pangan lokal, yang merayakan keberagaman rasa dan hasil bumi, adalah bangsa yang mengenal dirinya, mencintai tanahnya, dan memahami arti syukur.
Dari piring makan, sesungguhnya lahir kesadaran politik. Apa yang kita pilih untuk dimakan, dari mana asalnya, siapa yang memproduksinya, menjadi bagian dari pilihan moral. Makan produk lokal berarti memberi kehidupan bagi petani sendiri. Menyisakan makanan tanpa rasa bersalah berarti menumpuk dosa ekologis. Maka, setiap keputusan di meja makan sejatinya adalah keputusan kebangsaan.
Jika pendidikan membentuk pikiran, maka pangan membentuk watak. Cara kita menghargai makanan, cara kita berbagi, bahkan cara kita menolak lapar orang lain, adalah ukuran keadaban. Dalam budaya Nusantara, makan selalu diiringi nilai: “mangan ora mangan asal kumpul” — ungkapan yang menyiratkan bahwa kebersamaan lebih penting dari kemewahan hidangan. Di Sulawesi, orang Bugis mengenal siri’ dalam pangan—malu jika makan tanpa berbagi, malu jika kenyang di atas lapar orang lain.
Kini, bangsa ini dihadapkan pada paradoks: di satu sisi, pangan berlimpah di pasar; di sisi lain, banyak keluarga menahan lapar. Data, kebijakan, dan indeks ekonomi sering kali menutupi kenyataan moral itu. Maka, politik pangan seharusnya bukan hanya soal ketersediaan, tetapi juga soal keadilan—siapa yang makan, siapa yang menanam, dan siapa yang diuntungkan.
Sudah saatnya kita memulihkan makna pangan sebagai cermin peradaban. Pemerintah harus memandang pangan bukan semata urusan kementerian teknis, melainkan fondasi ideologi nasional. Pendidikan harus mengajarkan anak-anak mengenal tanah, menghormati petani, dan mencintai cita rasa lokal. Media harus mengangkat kisah pangan bukan sekadar resep, tapi narasi kebudayaan. Dan kita—setiap orang yang duduk di depan piringnya—harus belajar kembali untuk bersyukur, bukan sekadar kenyang.
Pangan bukan hanya apa yang kita makan, tapi bagaimana kita hidup. Ia adalah doa yang menjelma menjadi nasi, kerja keras yang menjelma menjadi roti, kasih yang menjelma menjadi rasa. Maka, ketika kita menata masa depan bangsa, mulailah dari menata piring kita. Sebab di sana, di antara butir nasi dan tetes keringat petani, peradaban sedang bercermin—mencari wajah aslinya yang mungkin telah lama terlupakan.
— Muliadi Saleh (Esais Reflektif, Pemerhati Pangan dan Direktur Eksekutif SPASIAL)